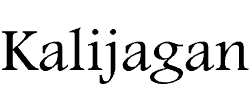Pernah suatu sore yang tidak saya ingat lagi tanggal dan bulannya, bersama Gus Aniq, saya dolan ke Demak, ke rumahnya kang Ahyar. Sore sangat terang. Selesai salat ashar kami berangkat dari Semarang. Perkiraan kami sampai di tujuan selesai magrib. Gus Aniq mewanti agar saya melaju motornya kalem saja agar tidak sampai di tempat tujuan habis magrib persis. “Orak kepenak mertamu ning desa wayah magrib,” kata Gus Aniq.
Perjalanan kalem itu kami tempuh dengan mampir ke warung bakso di Mranggen dan berhenti di sekitar mushala di salah satu desa di Demak untuk salat magrib. Dua adegan mampir itu kami sengaja agar bisa menunda kedatangan kami di tempat tujuan tidak tepat persis selesai magrib. Tetapi, tampaknya kami masih meyakini oleh pepatah lawas “manusia berencana, Tuhan memutuskan.” Kami tiba di depan rumah Kang Ahyar ketika suasana desa masih sangat sepi. Pintu-pintu rumah masih banyak ditutup. Saya mengetuk pintu rumah Kang Ahyar beberapa kali tapi tidak mendapat jawaban. Tampaknya sedang ada pengajian di mushala. Gus Aniq lalu mengajakku mencari tempat duduk untuk merokok sembari menunggu Kang Ahyar.
Di tempat duduk, kami merasakan suasana yang berbeda. Kami merasakan ketenangan. Suasana sepanjang jalan Semarang menuju Demak yang ramai dan berdesak-desakan yang kami rasakan tadi. Kini tidak tampak lagi suasana keramaian dan kebisingan itu. Magrib di suatu desa di Demak menenggelamkan suara-suara mesin-mesin transportasi dan industri. Semua tampaknya berhenti bekerja. Atau lebih tepatnya telah diminta si empunya untuk berhenti karena si empunya akan menjalankan rutinitas spiritual ketika magrib menjelang.
Dua manusia yang tampak asing yang duduk di pinggir jalan sembari merokok sering mengundang tatapan mata curiga dari para warga yang secara tidak sengaja lewat dan melihat kami berdua. Dua manusia berwajah asing itu memang patut dicurigai karena mereka tidak seperti kelakuan warga pada lazimnya. Dilihat dari busananya saja, kami sudah seperti orang dari seberang kota. Sebab, di antara para warga yang berlalu lalang mengenakan sarung, kami mengenakan celana jins dan kaos yang berbalut jaket. Ditambah kedua helm yang nangkring di spion motor semakin meyakinkan orang-orang kalau kami habis menempuh perjalanan jauh.
Perbedaan mana penduduk setempat, mana tamu sudah terlihat dari busana yang kami kenakan. Dan, barangkali juga didukung waktu kita berkunjung. Itu bertepatan dengan para penduduk pergi ke mushala untuk salat magrib dan mengaji alquran. Semua busana untuk pergi bekerja ke sawah, pabrik, kantor, bakal diganti dengan seperangkat sarung, baju koko, dan peci. Hampir semua mengenakan busana seperti itu. Bahkan ada kesadaran untuk memaknai peralihan sore menuju malam yang di tengah-tengah ada magrib. Mereka mengisinya dengan menghadap pada Tuhan.
Kesadaran memaknai waktu itu yang semakin mempertebal perbedaan dua manusia yang duduk di tepi jalan dengan penduduk warga setempat. Antara sarung dan celana. Kaos dan kemeja. Hingga pada menjelang isya dari sekian mata yang menatap kami dengan agak curiga. Seseorang dengan nada santun menghampiri kami dan bertanya, “Ngentosi sinten Mas?” Kami menjawab sedang menunggu Kang Ahyar. Dan, orang yang bertanya itu entah pergi ke mana, apakah ia pergi mushala menyusul Kang Ahyar untuk mengabarkan kalau ada orang yang mencarinya, saya tidak tahu. Yang jelas sekian menit setelah orang yang bertanya tadi menyapa kami, kang Ahyar menghampiri kami.
Ini adalah pengalaman saya yang kesekian kali menikmati suasana magrib di Demak. Rasanya saya selalu bertemu dengan suasana yang sama. Bapak-bapak yang sudah besiap dengan baju koko, sarung, dan pecinya. Ibu-ibu dengan rukuhnya. Dan, bocah-bocah yang dengan cara cengesan dan guyon sekenanya pergi ke mushala. Itu adegan rutin yang sering terjadi setiap magrib datang. Di Demak khususnya, di desa-desa seluruh Indonesia umumnya.
Magrib itu terlalu sakral untuk dilewatkan dengan aktivitas lain selain pergi ke mushala untuk salat dan mengaji. Semua kesibukan kerja yang tampak membuat dunia begitu cepat, sumpek, dan berisik. Menjelang dan setelah magrib, waktu itu mengembalikan manusia untuk meninggalkan urusan duniawinya dan kembali ke waktu-waktu spritual. Yang kita rasakan pada waktu sakral itu adalah keheningan dan ketenangan orang-orang beribadah. Di Demak ini terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan, tidak terkecuali masa yang akan datang.
Lima bulan setelah perisitwa saya berkunjung ke rumah Kang Ahyar. Dalam perjalanan pulang dari Semarang menuju Jepara. Saya disambut tugu Alquran yang berada di sisi kiri jalan sebelum jalan lingkar. Saya terhenyuk sebentar. Di bawah Alquran ada kalimat ampuh: “Magrib, matikan televisi. Ayo mengaji!” (koreksi jika saya salah mengingatnya).
Saya tidak tahu sejak kapan tugu ini berdiri. Dan, merasa sangat wajar setelah sekian hari tugu itu berdiri tidak ada nada protes atau sedikit sinis dari warga Demak dengan pendirian tugu dan kalimat yang tertempel di bawahnya. Sebab mereka memang tidak merasa tersindir dengan kalimat itu. Bahkan mereka tidak tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Kalau seandainya kalimat itu ditujukan kepada warga Demak? Tampaknya kita perlu piknik sejenak ke desa-desa di Demak menikmati sore dan magribnya. Mereka sudah mematikan televisi dan menghidupkan mushala ketika magrib datang. Jauh sebelum anjuran itu diberikan pemerintah. Dan untuk sekadar mengaji di saat magrib mereka sudah melakukannya sedari dulu karena kesadaran bukan suruhan. Terkadang pemerintah itu sering mengajak kita bercanda dengan cara-cara yang tidak kita duga. Salah satunya menyuruh orang-orang matikan televisi dan mengaji saat magrib di tengah kehidupan warganya yang sudah terbangun dengan alam religiusitas yang kuat.
Saya pun jadi ingin kembali merasakan suasana keheningan dan ketenangan suasana magrib di desa Demak.