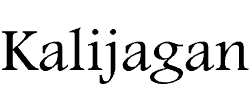Langit Demak cukup cerah pagi itu. Di ruang pamer rumah Benawa buku-buku dan majalah dengan kaver Mbah Nun masih tertata rapi. Gambar-gambar kliping yang tergantung pada figura menempel pada dinding-dinding berwarna hijau. Pagi itu pukul 10.00 WIB (28/05) akan dilaksanakan diskusi membincang Mbah Nun dari berbagai segi. Mengapa berbagai segi? Karena dimensi Mbah Nun begitu luas, ia masuk pada bidang sastra, drama, musik, sosial kebudayaan, pengajian, konsultasi, dan lain-lain.
Diskusi pada pagi itu dimoderatori oleh Kang Akhyar. Ia adalah penggiat Kalijagan. Ia terlebih dahulu bercerita tentang maksud diselenggarakannya acara “Pameran Buku dan Kliping; Mbah Nun, Maiyah, dan KiaiKanjeng ini. “Dari kliping-kliping itu terlihat dengan nyata dan jelas bahwa perjalanan bangsa ini tidak terlepas dengan sosok Mbah Nun. Anak-anak harus tahu itu. Mbah Nun dengan segala aktivitasnya yang padat dan tanpa henti mulai dari tahun 70-an hingga sekarang menjadi bagian penting bagi perjalanan Indonesia. Ini penting dan harus diketahui oleh generasi muda sekarang. Atas itulah kegiatan ini diselenggarakan.”

Selanjutnya Maulana Malik Ibrahim, pembicara pagi itu yang juga kolektor buku Mbah Nun yang koleksinya juga ikut dipamerkan di situ menyampaikan upayanya mengumpulkan karya-karya Mbah Nun atau segala hal terkait Mbah Nun yang berwujud teks, bisa potongan berita, buku yang pengantarnya Mbah Nun, hasil wawancara dll. Ia mengaku mendapatkan buku-buku tersebut dari toko buku loak dan pasar online. Kata Malik, “Akhir-akhir ini buku-buku lawas Mbah Nun di pasar online harganya naik tinggi, terutama buku-buku yang belum terbit ulang. Kegiatan semacam ini mungkin salah satu penyebab para penjual menaikkan harga jual bukunya.”

Satu hal lagi yang ditemukan oleh Malik adalah, sangat jarang ditemukan buku-buku bajakan karya Mbah Nun, terutama buku-buku lawasnya. Hal ini bisa dibandingkan dengan pengarang-pengarang lain yang bukunya banyak dibajak. “Apakah mereka takut kualat, tidak mendapatkan berkah? bisa saja.”
Lalu Prof. Harjito menyampaikan membaca Mbah Nun ini bisa melalui karya-karyanya saat usia muda. Esainya diterbitkan pertama di Horison pada tahun 1975, esai itu ditulis pada tahun 1973. Artinya jika dihitung mundur maka tulisan Mbah Nun telah dimuat di Horison pada usianya yang baru 20-an. Ia luar biasa mengingat Majalah Horison pada waktu itu adalah majalah sastra yang sangat disegani. Semua orang yang bermimpi menjadi sastrawan berlomba-lomba bisa dimuat di sana. Padahal sebelum dimuat di Horison karya-karya beliau telah dimuat terlebih dahulu di media-media lokal di Yogyakarta. Cerita-cerita Mbah Nun yang tertuang dalam puisi maupun cerpen adalah dialog tentang kedirian. Yang jelas melihat sepak terjang beliau yang memasuki banyak ranah itu menunjukkan bahwa dirinya adalah multi talent. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dia mampu mengelola energinya? Lalu tempaan semacam apakah yang membuat pribadi semacam itu? Tentu saja tempaan tersebut tidak di sekolah karena kuliahnya tidak lulus. Melihat itu kemungkinan keluarga Mbah Nun di Jombang dulu dari kakeknya, dari orangtuanya yang sudah memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Waktu Mbah Nun kecil di rumahnya sudah banyak digunakan untuk aktivitas sosial dan pendidikan, di rumahnya sudah ada perpustakaan. Lalu mungkin sistem pendidikan Gontor cukup membentuknya juga, juga kehidupan Jogja dimana Mbah Nun tumbuh dari Persada Studi Klub juga mendidiknya. Gemblengan-gemblengan tersebut membentuk manusia Emha Ainun Nadjib.

Sementara itu Gus Aniq yang pada pagi itu ikut diskusi menyampaikan, bahwa ilmu Mbah Nun ini adalah ilmu tua, ‘ilmu sepuh’. Meskipun beliau masih muda pada waktu itu tetapi visinya itu sudah visi tua. Hal ini mengindikasikan bahwa beliau ini terhubung dengan orang-orang sepuh.
Menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Prof, Harjito, Widyanuari Eko Putro, salah satu peserta diskusi pada siang itu mengatakan bahwa tentang kedirian ini adalah subjek yang melihat, subjek yang menilai. Hal ini dari sebuah perjalanan panjang. Ia bercerita tentang sejarah sastra. Sastra sebelumnya bercerita tentang orang-orang kulit putih karena Indonesia yang terjajah. Lalu orang-orang pribumi itu membaca dan bertanya, “Kok tidak ada saya disana?” saya dalam konteks ini adalah orang pribumi tidak diceritakan dalam cerita-cerita itu. Lalu mereka menulis sendiri, yang ditulis adalah tentang kedirian mereka masing-masing. Demikian juga dengan Mbah Nun ini, ia bercerita tentang kediriannya, apa yang dia lihat dan pandang. ia melihat orang mengenakan jilbab dilarang maka ia menulis lautan jilbab, ia melihat kasus Kedung Ombo, lalu ia menulis naskah drama Pak Kanjeng. Masalahnya cerita tentang kedirian itu, sebagai subjek yang memandang itu menjadi berurusan dengan pihak-pihak terkait seperti kekuasaan misalnya.
Acara diskusi pada hari itu dihadiri berbagai kalangan, ada sastrawan Demak Mbak Dian Nafi, Akademisi seperti Ibu Dr. Lina Putri Yanti, Komunitas Tanbihun dan RKSS, dll.