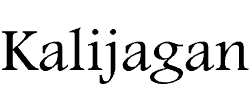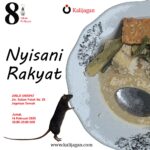Bagi seseorang yang pernah/sedang belajar tentang Kerajaan Demak, barangkali tidak ada yang tidak menyisakan satu pertanyaan klise perihal residu kejayaan peradaban yakni keraton kerajaan. Keberadaan Masjid Agung Demak dan Makam Waliyullah Raden Syahid Sunan Kalijaga dirasa belum cukup memenuhi hasrat pengetahuan publik. Banyak upaya telah dilakukan dalam rangka pencarian, baik secara arkeologis maupun metafisika.
Bukti arkeologis yang ada belum dapat memastikan eksistensi fisik keraton sesuai ekspektasi publik jika mengoperasikan dengan keberadaan bentuk keraton-keraton nusantara yang masih berdiri sekarang ini. Penemuan benda purbakala berupa ‘umpak’/penyangga tiang bangunan di kawasan Setinggil seakan makin menyisakan misteri yang untuk sementara terbungkam rapat di museum kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Di samping penemuan tersebut, berbagai upaya metafisika ditempuh oleh mereka yang ‘linuwih’ dengan hasil yang enggan dipublikasikan kepada khalayak. Alhasil, bola spekulasi tentang letak pasti Keraton Kerajaan Demak makin liar.
Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan terkait dengan keberadaan Keraton Kerajaan Demak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Gejala faktual menunjukan bahwa rasa penasaran oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut tidak dilanjutkan dengan upaya sungguh-sungguh untuk menemukan titik pasti juga bentuk fisik. Tidak ada upaya arkeologis secara massif untuk melakukan aktivitas kepurbakalaan seperti ekskavasi besar-besaran guna menyibak misteri yang ada di balik permukaan bumi Kesultanan Bintoro Demak. Bisa jadi rasa penasaran tersebut sudah tidak relevan lagi seiring dengan dinamika global yang tentu lebih menghendaki penyingkiran-penyingkiran hal yang tidak memiliki daya ungkit ekonomis secara signifikan.
Rasa ingin tahu dan upaya untuk menemukan bisa jadi makin meredup bahkan mati oleh karena berbagai alasan. Namun hal demikian seharusnya tidak berbanding lurus dengan meredup dan matinya kepedulian terhadap eksistensi Kesultanan Demak yang memiliki pengaruh tidak kecil terhadap peradaban dewasa ini. Dalam suatu kerajaan, keraton tidak sekadar simbol eksistensi kekuatan/kekuasaan, selebihnya adalah dinamisator peradaban dengan kompleksitas fungsi dari masing-masing komponen yang ada di dalamnya. Keraton memang memiliki dimensi fungsi hardware yang boleh jadi bisa terkikis zaman, di sisi lain keraton merupakan perangkat lunak yang dinamika kehidupannya dapat mengalami upgrading seiring dengan tantangan zaman.
Lantas, dimana titik letak Keraton Kerajaan Demak yang selama ini bersemayam di ruang penasaran siapapun yang ingin mendapatinya? Baiklah, akan coba dipaparkan hasil temuan setelah melakukan penggalian-penggalian terhadap permukaan kesadaran kepedulian, tentu dengan tingkat keluasan dan kedalaman yang barangkali masih terlalu sempit dan dangkal.
Rekonseptualisasi Kerajaan, Kesultanan, dan Keraton
Sebelum melalukan pembongkaran terhadap konsep kerajaan, kesultanan, dan keraton sebelumnya perlu dilakukan identifikasi terminologis terlebih dahulu terhadap ketiga istilah tersebut. Kata kerajaan, kesultanan, dan keraton adalah tiga kata benda yang sama-sama mendapatkan imbuhan ke dan an yang apabila diurai masing-masing bermula dari kata dasar raja, sultan, dan ratu.
‘Raja’ dan ‘sultan’ merupakan istilah lazim yang disematkan bagi seseorang yang sedang menjalankan roda kekuasaan pemerintahan bercorak monarki. Penggunaan istilah ‘raja’ di bumi nusantara dimulai tatkala penguasa-penguasa lokal mendapatkan pengaruh dari tanah Hindustan (India) pada awal-awal abad masehi. Masa-masa itu adalah momentum berkembang pesatnya ajaran Buddha dan Hindu yang secara sinergis dan harmoni mengalami peleburan dengan ajaran kepercayaan lokal.
Berbeda dengan ‘raja’, istilah ‘sultan’ merupakan penanda bagi penguasa yang menjalankan roda pemerintahan (kesultanan) di mana telah mendapatkan pengaruh pengaruh Islam khas Timur Tengah (Turki). Penggunaan istilah ‘sultan’ pertama kali tercatat dari bumi Sumatra khususnya di daerah Pasai. Perkembangan pengaruh Islam selanjutnya merambah pada wilayah Jawa di mana penggunaannya disematkan pada penguasa Demak yakni Sultan Fatah. Selain di Jawa, penggunaan istilah ‘sultan’ juga berlaku pada penguasa-penguasa di Kawasan Timur Nusantara (Sultan Hasanuddin, Sultan Nuku, dll.).
Berbeda dengan ‘raja’ dan ‘sultan’, istilah ‘ratu’ bermetamorfosis menjadi keraton setelah melakukan ‘lompatan terminologis’ yang sebelumnya seharusnya berbentuk ke-ratu-an. Istilah keratuan tidak mengalami popularisasi sebagaimana halnya istilah keraton. Imbas dari ketidakpopuleran tersebut adalah terjadinya pengaburan esensi makna ‘ratu’ yang tentunya memiliki hulu makna yang berbeda dengan ‘raja’ dan ‘sultan’ dalam perspektif seseorang yang menjadi penguasa. Istilah kerajaan dan kesultanan mengalami ‘linearisasi terminologis’ yakni konsisten dengan bentuk kata dasanya setelah mendapatkan imbuhan ke dan an. ‘Ratu’ merupakan istilah khas Jawa dengan pemaknaan mendalam lebih dari sekedar pemaknaan dari sudut pandang gender dengan konotasi suatu puncak kekuasaan yang diduduki oleh seorang perempuan.
Perbedaan asal usul tersebut sejatinya tidak perlu mengalami pereduksian kadar esensi karena ketiganya memiliki ketunggalan makna. Kaitannya dengan Demak, ketiga istilah tersebut sah-sah saja diterapkan dalam konteks yang sama apabila merujuk pada kesatuan institusi wilayah kekuasaan (Kerajaan Demak/Kesultanan Demak/Keraton Demak). Dua istilah pertama (kerajaan/kesultanan) oleh masyarakat dipahami sebagai kesatuan sebuah sistem roda pemerintahan dengan segala kompleksitasnya, sedangkan istilah keraton merujuk pada suatu tempat di mana para pemangku kebijakan beserta kerabatnya menetap/bermukim. Esensi makna antara sultan/raja/ratu adalah seseorang yang tengah menjalankan amanat secara sadar bahwa mereka adalah khalifatullah (representasi kekuasaan Tuhan) di dunia. Kerajaan/kesultanan/keraton adalah konsep tentang penempatan Tuhan oleh manusia di dalam ruang kesadaran dan tindakan dirinya. (Khoirul Anwar).