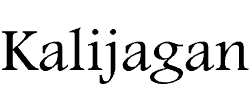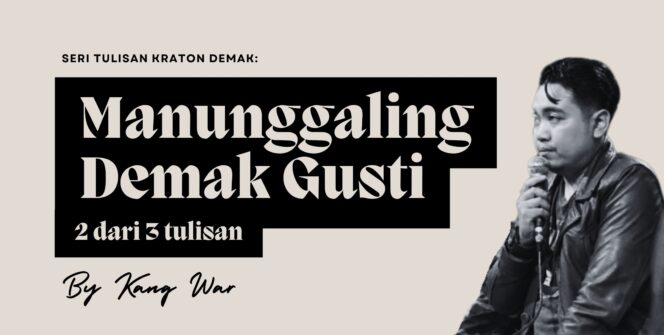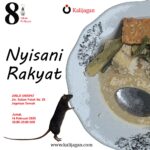Frasa Manunggaling Demak-Gusti terinspirasi dari istilah Manunggaling Kawula-Gusti yang oleh awam disebut sebagai ajaran Syaikh Siti Djenar, sosok ‘alim yang hidup pada era Walisongo. Sejatinya itu bukan ajaran dari Syaikh Siti Djenar, ibarat Ir. Soekarno sebagai penggali ajaran Pancasila, dirinya pun berada pada kedudukan serupa meski dengan peran yang tak sama. Dalam Islam ajaran tersebut merupakan intisari tauhid, yaitu penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Penyatuan dalam hal ini bukanlah peleburan dua unsur berbeda, namun pendudukan kesadaran manusia terhadap keberadaan Tuhan. Simpulannya, Tuhan merupakan dzat yang tak teringkari oleh kesadaran manusia. Tidak hanya terbatas kesadaran, eksistensi Tuhan juga terwujud melalui segala tindakan manusia, itulah manunggal yang paripurna.
Terminologi manunggal hendaknya diberikan ruang kemungkinan untuk mengalami perluasan makna, bukan hanya sekadar ‘label sesat’ oleh pihak yang tidak tahu bahkan tidak mau tahu. Pada bagian sebelumnya istilah manunggal lebih didudukkan pada bangunan vertikal, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan. Namun pada bagian ini, istilah manunggal akan coba didudukkan pada bangunan horisontal yakni hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Pada tahap selanjutnya, akan coba dielaborasikan dengan konteks ke-Demak-an.
Sebelum melangkah lebih jauh, istilah Demak perlu ditempatkan pada satu titik untuk selanjutnya agar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang/paradigma. Dari sekian banyak sudut pandang, Demak mari kita sorot dari sudut pandang manusianya. Konteks manusia tentunya sangatlah kompleks, mulai dari historisitas sampai pandangan hidup. Dibutuhkan penjelasan hingga berjilid-jilid tak terhingga untuk membongkar timbunan misteri tersebut, namun dengan segala keterbatasan akan dicoba digali dengan keluasan yang masih terlalu sempit dan dan kedalaman yang masih amat dangkal.
Demak secara geografis memiliki karakteristik sebagai wilayah pesisir yang memiliki letak strategis. Sebagai wilayah pesisir, Demak relatif mudah terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan yang berada di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan jalur transportasi besar kala itu. Di samping berkedudukan pada wilayah pesisir, Demak juga berpotensi sebagai penghasil produk-produk agraria mengingat kondisi tanahnya yang subur karena dilalui Sungai Tuntang. Hilir mudik/lalu lalang moda transportasi laut/darat memungkinkan terjadinya berbagai pergerakan arus, barang, jasa, termasuk pengetahuan.
Peran Walisongo dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari riwayat keberadaan Demak. Islam pada masa awal perkembangan di Demak ditumbuhkan-kembangkan melalui medium pendidikan dan kebudayaan. Alasan logisnya adalah pada awal pendudukannya di Demak, Raden Patah yang merupakan murid Sunan Ampel tidak mendirikan pos-pos pertahanan militer melainkan pesantren dan masjid. Pesantren dan masjid tidak hanya sekadar menjadi pusat pendidikan dan peribadatan, selebihnya keduanya adalah medium peradaban bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini, Walisongo memegang peranan yang amat penting sebagai dinamisator perubahan kondisi kehidupan di kawasan Glagah Wangi.
Lantas mengapa Raden Patah mendirikan pesantren dan masjid, bukan pusat kekuasaan dengan dengan segala atribut pertahanan wilayahnya? Secara genealogis Raden Patah memang masih keturunan Prabu Brawijaya. Namun kondisi awal kiprah, Raden Patah tidak memiliki ambisi untuk berkuasa melainkan memperluas dan memperdalam ilmu agama. Perjalanan dari Palembang menuju Jawa pada akhirnya mempertemukan Raden Patah dengan Sunan Ampel yang berbasis di Pesantren Ampel Denta. Pesantren adalah pusat pendidikan bukan pusat kekuasaan, maka persebaran para santrinya setelah menempuh/menyelesaikan pendidikan adalah mendirikan pusat pendidikan lain di wilayah yang baru.
Demak oleh Walisongo dipersiapkan sebagai wilayah pusat kebudayaan. Hal demikian dilatarbelakangi oleh kondisi Majapahit yang makin meredup kejayaannya sepeninggal Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajahmada. Untuk menjadi suatu pusat kebudayaan, Demak memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang otonom. Walisongo menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat akomodatif yakni tidak mengeliminasi budaya lokal. Seni pertunjukan dan tasawuf menjadi saluran efektif Islamisasi Demak yang pada tahap selanjutnya secara massif tersebar ke penjuru Nusantara.
Kebudayaan adalah sarana manunggal antara manusia dengan anasir-anasir semesta. Kemanunggalan manusia dengan Tuhan ditempuh melalui jalur tasawuf yang berorientasi pada ke-tauhid-an. Kemanunggalan manusia dengan sesamanya kadang kala memiliki tingkat kerumitan tertentu mengingat keunikan manusia itu sendiri dalam menciptakan struktur tatanan sosialnya. Secara historis terbukti bahwa Demak gagal bertahan sebagai peradaban besar melalui saluran perluasan kekuasaan, khususnya pada era pasca Sultan Trenggono. Justru yang terjadi adalah penurunan pamor secara drastis sehingga terjadi peralihan konstelasi politik yang pergerakannya menuju daerah pedalaman. Dengan demikian kekuasaan bukan merupakan sarana kemanunggalan antar sesama manusia, terlebih lagi antara manusia dengan Tuhan.
Walisongo mungkin menyadari bahwa menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan merupakan bukan langkah yang tepat. Meskipun pada tahap berikutnya Demak bergerak di bidang politik, namun itu bukan merupakan tujuan karena kebudayaan adalah titik berat penyebaran Islam. Kebudayaan sebagai orientasi Islam bermakna Walisongo mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang berbudi-daya. Dengan konsistensi tata laku demikian, Demak tidak hanya sekadar sebagai satuan wilayah administratif selebihnya sebagai satuan budaya. Sebagai satuan budaya, Demak secara ideal seyogyanya memiliki pandangan hidup berorientasi kemanunggulan dengan Tuhan melalui kemanunggalan manusia dengan sesamanya. Kebudayaan adalah sarana yang tepat untuk terwujudnya kemanunggalan tersebut.