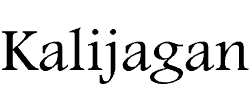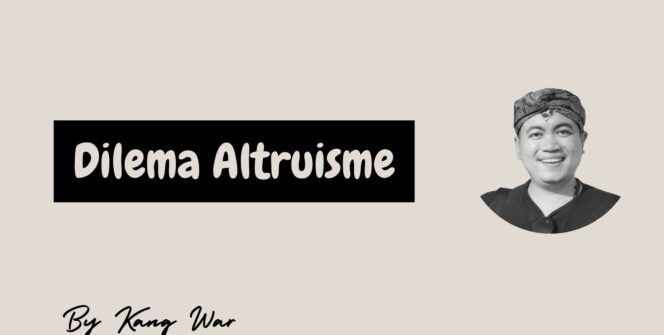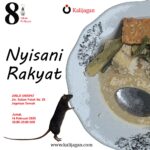Sebuah keluarga di kota Pasuruan (Provinsi Jawa Timur) mempunyai tradisi zakat setiap tanggal 15 Bulan Ramadhan. Kebiasaan itu dilakukan mulai tahun 1975 dengan “mendatangkan” ribuan warga untuk berkumpul di depan gerbang kediaman megahnya. Diketahui keluarga tersebut berlatar belakang mentereng sebagai pengusaha sarang burung walet, pengepul kulit sapi, dan menggurita hingga bisnis otomotif. Sejak tahun pertama, pembagian zakat berjalan tidak menimbulkan masalah berarti. Sampai pada 2008, suatu kejadian yang tidak dapat terhindarkan pun terjadi. Seperti yang sudah-sudah, pengumuman pembagian zakat disebarkan melalui siaran radio sehingga sejak sekitar pukul enam pagi warga Pasuruan dan sekitarnya mulai memadati kawasan kediaman sang “crazy rich”. Menurut keterangan, tidak ada mekanisme pengamanan representatif untuk “mengendalikan” ribuan warga yang mengantre demi nominal sebesar Rp 30.000. Jauh dari kata tertib, yang terjadi adalah kericuhan karena situasi berdesak-desakan agar bisa “saya duluan”. Alhasil, 21 mustahiq (penerima zakat) meregang nyawa dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat sesak napas dan tak sadarkan diri.
Sebenarnya insiden tersebut bukan tidak pernah terjadi, atau paling tidak gejalanya sudah tampak. Pada tahun sebelumnya keluarga tersebut juga membagikan zakat yang dilakukan setiap tanggal 15 bulan Ramadhan. Pada tahun 2007, pembagian zakat sudah terlihat mulai tidak kondusif sehingga menimbulkan beberapa warga tak sadarkan diri namun proses pendistribusian masih tetap berjalan. Rupanya sang “crazy rich” tidak belajar dari masa lalu. Tanpa koordinasi dengan pihak keamanan resmi, ia tetap mengundang kerumunan untuk sebuah “tindakan mulia” namun berakhir malapetaka. Dua puluh satu nyawa sekiranya cukup menjadi bahan pelajaran terakhir dari tahun 2008 yang tidak perlu mendapat “remedial”. Bukankah berbagi adalah kebenaran dan kebaikan? Namun mengapa masih ada celah yang mematikan diantara citra kedermawanan manusia yang juga dituntut tidak hanya memikirkan “dirinya sendiri”?
Apa yang melanda warga Pasuruan waktu itu merupakan fenomena sosial yang dikenal “altruisme”. Altruisme adalah tindakan sukarela yang dilakukan untuk kepentingan orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Ini adalah perilaku yang didorong oleh kepedulian dan empati terhadap kesejahteraan orang lain. Satu tahun pertama setelah sejak pembagian zakat itu dilakukan, pada tahun 1976 seorang ahli etologi dan biologi evolusioner Inggris bernama Richard Dawkins meluncurkan buku berjudul “The Selfish Gene”. Karya tersebut mengintroduksi pandangan evolusi yang berpusat pada gen, bukan pada individu atau kelompok. Dawkins berpendapat bahwa gen adalah unit seleksi alam, dan organisme hidup adalah “mesin kelangsungan hidup” yang diciptakan oleh gen untuk mereplikasi diri mereka sendiri. Konsep “gen egois” tidak berarti bahwa gen memiliki kesadaran atau niat, tetapi hanya bahwa gen yang berhasil mereplikasi diri mereka sendiri cenderung menjadi lebih umum dalam populasi. Dawkins menjelaskan bahwa perilaku altruistik (perilaku yang menguntungkan orang lain) dapat berevolusi jika menguntungkan gen yang sama. Meskipun individu mungkin tampak altruistik, gen yang mendasari perilaku tersebut sebenarnya “egois” dalam arti bahwa mereka mendorong perilaku yang meningkatkan peluang mereka untuk mereplikasi diri.
Dari Pasuruan kita beranjak ke Malmesbury, Wiltshire, Inggris, lebih tepatnya sekitar empat abad yang lalu. Seorang filsuf bernama Thomas Hobbes memberi uang recehan kepada pengemis. Seorang temannya yang melihat kejadian itu bertanya kepada Hobbes mengapa ia melakukan hal tersebut. Hobbes menjawab bahwa ia melakukan itu bukan karena merasa kasihan kepada si pengemis, namun sebab ia merasa tidak nyaman melihat pengemis tersebut. Dalam kasus ini, Hobbes memberikan uang kepada pengemis bukan karena ia peduli, tetapi karena ia ingin menghilangkan rasa tidak nyaman yang ia rasakan. Menurut Hobbes, manusia selalu termotivasi oleh kepentingan diri sendiri, bahkan ketika mereka melakukan tindakan yang tampak altruistik. Apa yang menjadi motif seseorang ketika memberi uang kepada seorang pengamen yang “menginterupsi” di tengah-tengah jam makan siangnya? Apakah itu sebagai bentuk apresiasi atas karya estetika yang ia persembahkan kepada seseorang itu? Atau itu adalah harga yang harus dibayarkan agar segera bebas dari “rasa tidak nyaman” oleh sebab seseorang itu memiliki selera musik yang berbeda dengan pengamen tersebut? Dalam beberapa hal Rousseau memang unggul atas gagasannya bahwa “pada dasarnya manusia adalah baik”, namun Hobbes dalam kasus ini tampaknya lebih unggul sebab manusia “tidak hidup di atas kertas”.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa aktivitas keluarga Pasuruan berderma tujuh belas tahun lalu adalah “tindakan egois”. Mereka sudah berupaya menjalankan “kebenaran” sebagaimana yang diperintahkan menurut ukuran dan aturan hukum Islam. Namun nilai sebuah tindakan tidak hanya berpegang pada parameter kebenaran. Ada ukuran lain yang perlu dipertimbangkan untuk dirujuk yaitu, kebaikan dan keindahan. Jika berbagi adalah kebenaran, mengapa masih berpotensi menjadi tidak baik dan tidak indah? Gus Baha dalam sebuah ceramahnya mengutip sabda Nabi Muhammad bahwa tatkala seseorang memberi kepada orang lain, maka si pemberi itulah “yang sebenarnya membutuhkan”. Sebab yang diberikan bukanlah sesuatu yang “dihilangkan” dari unsur pemberi, namun itu akan “yang abadi” di akhirat. Bukankah itu tindakan “menguntungkan diri sendiri”? Saya tidak bermaksud ajaran Nabi Muhammad tidak jauh berbeda dengan “sabda Thomas Hobbes”. Pemikiran Nabi Muhammad tidak hanya mempertimbangankan untuk kepentingan pribadi, namun didasarkan pada “wahyu Tuhan” yang menekankan “pentingnya bersyukur”.
Bersyukur adalah mekanisme yang diinstruksikan melalui perangkat institusional yang lebih mengacu pada “manifestasi norma”. Firman Tuhan menyebutkan bahwa dengan bersyukur “maka akan ditambahkan kenikmatan”, jika tidak bersiaplah untuk mendapatkan “ganjaran yang pedih”. Pemberian adalah elemen sistem keseimbangan untuk kehidupan yang memungkinkan mengarah pada tujuan komunal yaitu ekuilibrium sosial. Sebagaimana diketahui ketimpangan menjadi isu global yang merangsek hingga tataran akar rumput yang seolah senantiasa menerima takdir untuk siap “diinjak-injak” setiap saat. Jadi, zakat adalah tataran institusi sosial yang memiliki visi dan misi mulia yaitu memperpendek jarak kesenjangan antar individu yang diperintahkan Tuhan. Namun yang perlu diingat adalah itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kebenaran, kebaikan, serta keindahan. Bukankah itu akan lebih baik apabila dilakukan dengan mendatangi penerima secara satu per satu setelah melalui rapat panitia yang serius dengan melakukan seleksi yang “adil”? Bukankah itu akan lebih indah apabila memang terpaksa mendatangkan kerumunan dibentuklah suatu pengelolaan yang lebih “manusiawi” meskipun akan ada sedikit konsekuensi “pembengkakan anggaran”?
Kemudian, mengapa “si pemberi itu yang sesungguhnya membutuhkan”? Secara deduktif saya katakan itu bukan tindakan egoisme menurut cara berpikir Thomas Hobbes. Bagaimana jika kita coba menggunakan mental model “seteru abadi” nya Hobbes yaitu J. J. Rousseau yang menilai pada dasarnya “manusia adalah baik”. Jika manusia pada dasarnya baik, maka semua tindakan yang dilakukannya adalah representasi kebaikan. Itu premisnya. Lantas mengapa masih ada kejahatan? Mengapa seseorang perlu “dihukum” setelah dirinya dinyatakan “bersalah” sebagai wujud “hadiah” untuk mengembalikan tatanan sosial pada ekuilibriumitas yang dikehendaki? Pertama, kejahatan adalah nilai perbuatan yang dilakukan manusia dengan motif dan modus yang variatif. Kabar selanjutnya salah seorang anggota keluarga yang beperan sebagai “ketua panitia” insiden Pasuruan tersebut harus menjalani hukuman kurungan penjara karena “kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang”. Dia “tidak sengaja membunuh”, dan itu sudah dikategorikan sebagai “kejahatan”. Terkadang kejahatan bukan hanya sesuatu yang benar-benar direncanakan, namun bisa muncul sebagai tragedi yang terjadi sebab ketidakmampuan manusia “melihat masa depan”. Untuk penjelasan inti dari pertanyaan pertama adalah “apakah ada manusia yang benar-benar berniat untuk ingin menjadi jahat”? Kata Rousseau dalam “kontrak sosial” itu adalah “tindakan gila”. Kemudian, mengapa kita memberi? Jawabnya sebab kita masih memiliki “kewarasan”, dan itu adalah baik.
Kedua, jika manusia baik mengapa masih perlu ada hukuman? Kita coba jawab dengan pertanyaan, apakah ada manusia yang benar-benar ingin dirugikan? Jika Hobbes memandang “semua manusia adalah jahat”, maka pertanyaan itu sepertinya cukup untuk menggugurkan idenya. Namun ada hal baik dari pernyataan “egoisme” nya Hobbes, sebagaimana Rousseau bahwa masyarakat perlu tatanan yang “menyeimbangkan”. Publik perlu kesepakatan kolektif untuk mengatur ketertiban yang seharusnya didasarkan pada “prasangka baik” untuk mengantisipasi tindakan buruk, sebab kesalahan adalah “kerabat dekat” manusia. Jadi untuk apa hukuman itu? Sejatinya itu adalah untuk mengadili perbuatan, bukan mengganjar manusianya secara fisik-biologis. Maksudnya, jika ada seseorang yang merugikan orang lain dan dia mendapatkan hukuman, maka itu merupakan suatu kebenaran. Dalam konteks “welas asih”, kita justru perlu memberi empati terhadap setiap pelaku kejahatan sebab dia memiliki potensi untuk dijauhkan dari fitrah-nya sebagai manusia, yaitu sejatinya dia adalah baik. Jadi hukuman adalah kebenaran dan kebaikan yang memang perlu ada. Bukankah para penegak hukum adalah “figur altruistk” yang mengedepankan kepentingan umum atau lebih tepatnya memperjuangkan imparsialitas demi keadilan sosial? Penegak hukum juga manusia, yang tidak luput dari potensi apapun yang dia putuskan apakah demi kebenaran atau karena ingin “menghilangkan rasa tidak nyaman” yang ia rasakan? Merasa tidak nyaman apabila “miskin” misalnya.
Kemiskinan merupakan laju gerbong yang dihasilkan dari tarikan akumulatif antara symptom kesenjangan dan ketimpangan. Dua hal itu adalah gejala yang tidak mungkin tidak ada dalam sirkulasi sosial kemasyarakatan di manapun. Bisa dikatakan itu adalah jarak yang secara niscaya perlu ada demi harmoni yang “seirama”. Namun apabila jeda atau jaraknya terlampau jauh, maka akan berpotensi menjadi “lubang hitam” yang menyedot akal sehat baik “si kaya” maupun “si miskin”. Mengapa zakat perlu ada dalam konteks Islam? Sebab Tuhan memang menciptakan varian lain perbedaan yang disebut kesenjangan, supaya manusia memahami arti kemanusiaan yang semestinya ia jalankan. Bukan menjadi manusia yang “menggantikan peran Tuhan”, atau menjadi “Tuhan” itu sendiri. Kesenjangan adalah interval, semacam jarak pemisah yang memungkinkan alunan musik terdengar lebih merdu, membuat eargasm penikmatnya. Itu adalah juga semacam pemisah antara sepasang manusia yang sedang menjalani “hubungan jarak jauh” yang keindahan-keindahannya ada yang tidak bisa didapatkan ketika relasi itu terjalin terlalu dekat.
Nah, itu kata kuncinya. Semua yang “terlalu” memang tidak baik. Altruisme adalah pemikiran yang memungkinkan seseorang menjadi bagian dari “estetika sosial” yang terjalin tanpa merugikan siapapun, tanpa memandang “orang lain adalah jahat”, dan tanpa merasa dirinya “orang yang baik”. Namun kembali lagi, bahwa sejarah kadang memiliki cara bercanda yang “agak kelewatan”. Bukan sejarahnya yang “lucu”, namun perilaku aktornya yang “kocak”. Berbuat baik adalah karena memang perlu melakukannya, bukan sebab ingin “terkesan dermawan”. Dan itulah mengapa “kita yang butuh”, sebab kita sejatinya membutuhkan keseimbangan dan kesetimbangan sosial yang proporsional. Bukan kesenjangan dan ketimpangan yang semakin hari semakin menganga lebar. Tentu, jika itu terjadi maka sudah tidak ada yang diuntungkan lagi dari keberadaan manusia. Artinya, “kiamat semakin dekat”. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang berdaya guna? Jika tidak bisa, maka seiyanya tidak turut memperburuk keadaan. Semoga kita bisa belajar dari masa silam.
Semarang, 17 Ramadhan 1446 H